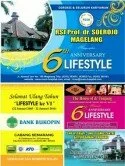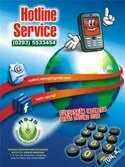P o t r e t
“Tamu Bu,” Bibi membungkuk santun.
“Siapa?” tanyaku sambil melipat koran, melepas kaca mata.
“Tidak tahu Bu, belum pernah ke mari.”
Aku mengangguk. Bangkit dengan benak penuh tanya, aku yakin tamu itu bukan teman bisnisku, karena ini hari Minggu. Bukan pula saudara, karena biasanya mereka menelepon lebih dulu memastikan aku ada di rumah. Mungkin saudara jauh atau teman lama yang tidak tahu adat kebiasaanku? Bisa jadi.
Begitu membuka pintu, kudapati seorang lelaki muda dan gadis kecil yang tengah bercanda di teras. Lelaki itu berkulit coklat terbakar matahari, berpakaian agak lusuh. Si gadis kecil berkulit lebih terang. Ketika gadis itu menoleh padaku, segera kutangkap sinar di wajahnya yang membuatku terkesiap. Sinar wajah itu tak asing bagiku. Meski bentuk hidung dan mata kedua tamu itu sama –yang membuatku bisa segera menyimpulkan bahwa mereka adalah bapak dan anak– namun kutemui sinar lain di wajah anak itu.
Lelaki muda itu menoleh ke pintu, ke arahku. Seketika dia berdiri, mengangguk sedikit dan mengucap selamat siang. Aku menjawab dengan sedikit goyangan kepala. Kupersilakan keduanya masuk, masih dengan jantung yang sedikit berdebar.
“Saya Hendra, Tante. Dan ini Nilna,” katanya sambil meletakkan tangannya di bahu gadis kecil itu.
“Maaf, mengganggu hari libur Tante,” katanya. Suaranya mantap dengan intonasi jelas. Kutatap dia lebih lekat, mencoba menjajaki lebih dalam siapa sebenarnya laki-laki di depanku itu. Dia cukup tampan. Mungkin kondisi ekonomi membuatnya kurang terawat dan tampak lebih tua dari usia sebenarnya.
“Saya ada titipan dari Nirma.”
Nirma. Dia menyebut nama itu! Seketika menegang otot-ototku.
“Maaf baru bisa menyampaikan sekarang,” lanjutnya. “Sangat terlambat, tetapi memang baru sekarang kami sempat ke kota ini.”
Dia keluarkan sebuah bungkusan pipih, diulurkannya padaku. Kuterima bungkusan itu dan kubuka salah satu sisinya. Foto kami. Aku, suamiku, Andreas, dan Nirma. Foto ketika dua anak kami masih kecil. Mungkin Nirma baru seusia gadis di depanku itu. Jadi Nirma yang telah mengambil foto ini dari ruang tengah, batinku.
“Nirma minta maaf tidak minta izin mengambilnya dan minta tolong saya mengembalikannya kemari.”
“Kenapa bukan dia sendiri yang mengembalikannya pada kami?” keramahan yang baru mulai muncul seketika sirna. Sikapku berubah dingin dan kaku. Ingatan pada Nirma, anak perempuanku itu telah membuka kembali luka masa lalu.
***
Masih jelas dalam ingatan betapa anak yang kukandung, kulahirkan dan kubesarkan itu tega menampar-nampar wajahku. Aku tak tahu, apa yang telah merasukinya. Nirma yang begitu manis, sedikit demi sedikit mulai berubah begitu masuk kuliah. Awalnya, hanya ikut kegiatan kemahasiswaan saja. Selanjutnya dia lebih banyak menghabiskan waktu bersama teman-teman di organisasi mahasiswa. Waktu itu aku mulai menegurnya. Kami sempat berdebat sebelum akhirnya tercapai kesepakatan bahwa aku tidak akan melarangnya berkegiatan selama dia mampu mempertahankan prestasi akademiknya.
Lama-lama dia mulai malas pulang. Rumah hanya dijadikan tempat singgah. Komunikasinya denganku menurun drastis. Aku yang dulu jadi teman ngobrol berubah menjadi kasir yang hanya ditemui pada saat butuh duit. Begitu jarangnya dia pulang hingga kadang aku terkaget-kaget ketika bertemu. Anak gadisku yang cantik, bersih, dan wangi tiba-tiba kutemui telah jadi malas merawat diri. Dia datang menemuiku dengan wajah tirus, mata lelah, dan baju yang apek. Bahkan pertemuan selanjutnya tidak kutemui lagi rambut hitamnya yang dulu lebat dan indah dengan poni yang membuatnya seperti boneka Barbie. Rambut itu telah dipangkas pendek karena dia merasa terlalu ribet mengurusnya.
Aku mulai punya alasan untuk marah dan melarangnya berkegiatan, tetapi dia membantah. Bahkan terang-terangan menyatakan sikapnya terhadapku. Mengkritik aku yang katanya otoriter, menjalankan kepemimpinan rumah tangga dan perusahaan sekehendakku, tanpa mau mendengar usulan dan suara ketertindasan orang lain. Siapa tak akan terbakar? Tahu apa dia tentang kehidupan rumah tangga? Apalagi tentang perusahaan. Tak sadarkah dia bahwa perusahaanlah yang membuatnya bisa hidup seperti sekarang?
“Perusahaan itu tumpuan hidup kita. Kamu tidak perlu mencampuri urusan Mama karena kehancuran perusahaan berarti kehancuran hidup kita,” kataku tajam.
“Ya, memang perusahaan itu yang membuat kita kaya-raya. Tetapi ingat Ma, para buruh itulah tulang punggungnya. Dan selama ini Mama dengan atas nama perusahaan telah memeras tenaga mereka tanpa imbalan yang sepadan,” teriak Nirma lantang.
Aku meradang. “Kalau tak suka dengan cara kerja Mama, jangan makan dari hasil kerja Mama. Pergi, carilah makan sendiri atau tetap tinggal di sini dan kunci mulutmu!”
Di luar dugaan, Nirma memilih keluar dari rumah. Meninggalkan kehidupan mapan kami dan menggantinya dengan kehidupan liar. Tidur di mana pun dan makan dari siapa pun. Pernah aku berniat menyusulnya karena tak tega, tetapi sebelum niat itu kesampaian dia justru memimpin demo karyawan menuntut perbaikan kesejahteraan. Maka tidak sekadar gagal keinginanku menjemputnya, tetapi lebur juga maafku untuknya. Sejak itu aku tak mau berpikir tentang anak itu lagi. Dia kuanggap sudah bukan anakku lagi! Ternyata kepergiannya waktu itu sambil membawa foto yang sekarang ada di tanganku ini.
“Kenapa tak dia kembalikan sendiri foto ini?” aku mengulang pertanyaanku dengan sisa kemarahan masa lalu.
“Dia tak bisa,” jawab Hendra.
“Kenapa?” tanyaku. “Takut bertemu Mamanya?”
“Bukan,” Hendra menggeleng lemah. “Dia tak bisa menemui siapapun lagi,” lanjutnya pelan sambil menahan napas.
“Sakit?” tanyaku masih dengan keangkuhan.
Hendra menggeleng. Tanpa menatapku dia berkata, “Nirma sudah pergi. Setengah tahun lalu.” Dan laki-laki di hadapanku itu mengusap air matanya yang mengambang.
Meski begitu terluka oleh ulahnya dulu dan meniatkan tak menganggapnya anak lagi, tetapi kabar ini mencabik perasaanku. Nirma…
“Maafkan, saya tak bisa menjaganya,” laki-laki itu telah mampu menguasai perasaannya. Sikapnya kembali tenang. “Semuanya berjalan begitu cepat. Suatu hari tiba-tiba saya jumpai Nirma muntah darah. Saat itu juga saya bawa dia ke rumah sakit. Beberapa hari di sana, dokter menganjurkan agar dibawa pulang saja. Kanker ganas di paru-parunya telah menjalar ke organ-organ lain dan tim medis sudah tidak bisa berbuat apa-apa,” dia berhenti sebentar, menghela napas. Kami saling diam beberapa saat lamanya. Masing-masing larut dengan kenangan dan penyesalan.
“Kau suaminya?” tanyaku kemudian dengan nada yang lebih lunak.
Dia menatapku sebentar sebelum mengangguk ragu. “Maaf, saya tak minta izin Tante lebih dulu.”
“Jadi ini anak Nirma,” kataku lirih, hampir pada diri sendiri. “Kalau boleh, biar aku yang mengasuhnya,” kataku tiba-tiba.
Hendra tersenyum. “Makasih Tante, dia adalah nafas saya. Jadi tak mungkin saya berpisah dengannya. Meskipun saya tak mungkin memberi kemewahan padanya.”
Aku cukup tertampar dengan jawabannya. Tapi kutahan tak memberi reaksi apa pun pada jawaban itu.
Tak lama kemudian laki-laki itu minta diri. Kuantar sampai pagar. Mereka pun berlalu. Masih sempat kulihat lambaian tangan mungil Nilna padaku yang kubalas dengan lambaian pula.
Aku masih berdiri di pagar sekalipun kedua tamuku telah lenyap bersama angkot yang membawa mereka. Tiba-tiba aku teringat, sebentar lagi suamiku pulang. Dan dia tak boleh tahu apa yang terjadi. Jadi segera kututup pagar dan melangkah masuk. Membasuh muka lalu kembali duduk di depan tivi, sambil membuka-buka halaman koran Minggu. ***