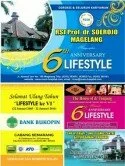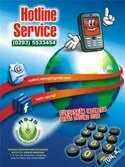Pertemuan
Pertemuan
By: Anna
Cinta tak selalu menampakkan sebuah rasa yang begitu nyata. Tak mesti ada debaran di dada, atau pahatan wajah yang terukir begitu jelas. Kau tahu?
“Aku mencarimu di antara rintihku…”
Tapi aku tak pernah menemukanmu. Jarum itu terlalu dalam terbenam dalam tumpukan jerami. Sepertinya kau memang selalu ingin datang dan pergi. Kucari kesana, kau bilang tak bisa. Ku cari kau kesini, kau pesan, temui aku nanti. Aku heran, kenapa rasa ini tak jua mau pergi.
“Mau jadi pacarku?” tanyamu.
Senyumku menjawab. Ah, kau kan selalu menggodaku dengan candaan yang tak bermutu, bahkan nyais membuatku malu.
Setahun berjalan.
“Aku punya pacar. Namanya Ninda,” riang suaramu.
“Selamat deh. Jangan lupa dijaga baik-baik,” ada rasa yang menyelusupkan perih di hatiku. Aku tak pernah keliru tentangmu. Setelah Andini, Mega, Nuning, Vicky, kini Ninda. Dan semua kembali berjalan seperti biasa. Sapamu masih menyapaku hampir tiap hari. Meski cuma pesan singkat.
“Haloo…!”
Aku tak ingin membalasnya. Kujaga perasaan kekasihmu. Atau, menjaga perasaanku sendiri?
Terakhir kali, sebuah undangan berpita ungu mengabarkan, akhirnya kau menikahi Ninda di pulau asalnya.
“Congratulation ya Fre. Tapi maaf banget, aku nggak bisa datang di resepsi pernikahanmu. Ada tugas kantor buat presentasi. Kamu nggak mau aku dipecat gara-gara mangkir dari pekerjaan kan? Hehe… Jaga s’lalu bahagiamu ya…!” kataku lewat telpon.
Tak kupungkiri, tugas kantor itulah penyelamatku. Bahagiaku membuncah kala kudengar suaramu, tapi hatiku tersayat mendengarmu bertutur tentang kebahagiaanmu bersamanya. Toh, kuping ini tak pernah bisa kututup. Kita bersahabat lebih dari 3 tahun. Aku tak tahu, apakah salah jika perasaan ini berubah.
***
Lima tahun. Yang kudapati sekarang bukanlah kau yang kukenal dulu. Semua mengubahmu!
Sarkastik. Selfish. Apatis. Apa yang dilakukan dunia padamu?
“Maafkan aku..” katamu. Itu tak menjelaskan apapun.
“Dunia tak menjanjikan apapun. Cuma kedok yang semua orang juga bisa melakukannya. Cinta? Huuuh…apa yang orang tahu tentang cinta? Mulut manis penebar bisa..?!” ada kilatan di matamu. Kamu marah, Fre. Aku tahu. Cinta menggoreskan pedang tajamnya, merembeskan luka yang tak mampu kau hentikan. Karmakah?
“Aku disini….” Tawarku.
“Terlambat, Sya..”
Keningku mengkerut. Terlambat untuk apa?
“Waktu adalah penyembuh, Fre. Yakinlah..”
“Siapa bilang? Aku telah mencobanya selama 3 tahun. Kau tahu apa yang kudapat? Penyakit menjijikkan ini!!!”
Terisak bibirmu bergetar mengenang sejarah penyakit itu menghuni jiwamu. Meski kini kau berontak. Tapi kau tak bisa mengelak. Tuhan, pantaskah Kau hukum Fre seperti ini?
‘Aku cinta kau, Fre…’ rasanya kata-kata itu tak kan sanggup lagi kukatakan. Fre terpuruk. Luka itu membenamkannya dalam dunia yang tak pernah dikenalnya.
‘Aku cinta kau hingga kini…’
Perih. Aku menangis untukmu. Sekalipun kau tak pernah tahu, kusimpan cinta ini selama bertahun-tahun. Kepada angin kukabarkan, kurindu ceritamu. Kepada kawan kutanyakan, tak ada yang tahu. Kau lenyap ditelan bumi, hingga pencarianku terhenti.
***
Tuhan menciptakan
Dua mata untuk melihat,
Dua tangan untuk bergandengan,
Dua kaki untuk berjalan,
Dua telinga untuk mendengarkan,
Tapi mengapa cuma satu hati?
Itu agar kita bisa saling melengkapi
Dengan sebuah cinta sejati
Kutuliskan kalimat itu tanpa alamat. Aku hanya sekedar ingin menulis saja. Aku juga tak berharap suatu saat kau akan membacanya. Mungkin kau telah menemukan dunia yang jauh lebih membahagiakan. Tanpa saling usik. Hingga aku tak mengenalimu lagi.
Sampai pada sore itu.
Sebuah pertemuan kau tawarkan. “Bisakah kita bertemu besok sore?” terbaca di layar ponselku. Nomor tak dikenal.
“Maaf, siapa ya?” mungkin klien yang ingin membicarakan proyek baru, harapku.
“Fre…”
Fre?! Antusias kupencet tombol untuk memberi jawaban,”Jam brp? Di mana?”
Perasaanku tak karuan. Ini adalah kabar pertama setelah enam tahun berlalu. Tiba-tiba kau ingin bertemu denganku. Ada apa?
Tak lama ponselku bergetar lagi: “Di café Zest, sore selepas kerja.”
Zest, café tempat kita dulu biasa ngobrol bareng teman-teman tiap week end. Atau kita berdua saat ingin ngobrol soal pribadi, tentang teman-teman wanitamu terutama. Kau tak pernah protes meski aku menjulukimu ‘playboy kampung’.
“Bodo amat! Yang penting kamu masih mau diajak jalan kan? Udahlah, tak usah pusingin gossip. Ngapain dibikin pusing? Aku akan sembuh setelah kau jadi pacarku,” sahutmu enteng.
Jadi, ajakanmu kali ini, rasanya akan jadi pertemuan antara dua bayangan masa lalu yang terpenggal, lalu secara perlahan kembali dipertemukan oleh waktu. Dua bayangan itu tiba-tiba saling mendekat, tanpa kita pernah merasa kalau kita sebenarnya telah dekat. Seperti pertemuan dua muka, dan dua telapak tangan yang terlihat dalam cermin.
Pertemuan kami seperti takdir. Aku hanya berani bilang “seperti” karena takdir itu sebenarnya bukan milik kami. Sebuah takdir yang terus menjaga perasaan, yang tersimpan bertahun-tahun tanpa harus bisa berbuat apa, lalu menghadirkan kembali di saat yang entah benar atau tidak. Sebuah takdir yang mampu membuat sebentuk pertemuan indah seperti pertemuan mentari dan batas cakrawala yang selalu menawarkan keindahan berbeda, saat pagi dan senja.
***
Sore yang dijanjikan itu datang. Aku mengambil tempat di sudut, tempat kita biasa menghabiskan waktu. Aku menunggu Fre, menunggu kenangan, dengan cemas dan penuh harap. Aku hendak menelepon, memastikan pertemuan ini. Nomor ponselnya sudah tertera di layar. Namun dalam batin terjadi perang antara ’ya’ dan ’tidak’. Akhirnya aku pencet tombol merah, aku tak jadi meneleponnya. Aku hanya ingin dengar suaranya langsung dan berdenting indah.
Sebuah pesan singkat masuk lagi: “Aku agak telat, ada rapat kecil evaluasi. Tunggu dulu….”
Jadi Fre sudah pindah lagi ke kota ini? Kok aku tak tahu?
Aku me-replay: “Tak apa, selesaikan dulu pekerjaanmu.”
Di ujung jalan, terlihat senja mulai turun. Merah keemasan. Waktu terus beringsut hingga berada di antara bibir senja dan malam. Cahaya mentari mulai meredup digantikan sinar-sinar elektronik. Udara sedikit sejuk. Aku mulai resah.
Bukan karena menunggu Fre. Tapi pertengkaran hatiku sendiri. Aku masih punya waktu untuk membatalkan pertemuan ini. Jantungku berdegup kencang. Pantatku mulai panas. Benakku terus dipenuhi pertanyaan: apakah aku harus meninggalkan tempat ini?
Mungkin aku dan Fre punya bayangan yang sama tentang masa lalu. Memendam kekaguman tanpa harus banyak bicara. Menyimpan rasa tanpa harus tahu ke mana jejaknya akan pergi. Tetapi apakah sebuah kekaguman itu harus dibicarakan? Aku rasa tidak. Rasa akan dijawab dengan rasa, jiwa akan dibalas dengan jiwa. Bukankah ini adalah rasa dan jiwa kita berdua? Sebuah kekaguman, keinginan, rasa, dan jiwa yang kemudian dipertemukan. Aku ingin menikmati semuanya ini sendiri, dengan rasa, dengan jiwaku. Seperti menikmati lengkingan saxophone Kenny G yang getir dan menyayat di malam-malam yang basah. Hidup memang penuh kenangan, sambung-menyambung dengan kisah lain. Kadang terangkai dengan sempurna hingga kita selalu menginginkan kenangan itu datang lagi. Kadang pula tercabik di sana-sini, dan meninggalkan perih yang mengiris. Aku menjadi bagian dari kenangan itu. Menjadi sepotong scene dalam episode kehidupanmu meski tak tahu akan kau letakkan di intro, reffrain, atau ending. Atau mungkin menjadi bagian interlude yang bisa timbul-tenggelam.
Lalu anganku buyar. Kupandang sesaat kursi kayu di depanku, tempat duduk Fre tujuh tahun lalu. Kupencet tombol ponsel. “ Aku tak jadi bertemu…”
Kutinggalkan café dengan langkah ringan. Aku bahagia, dengan apapun keadaanku sekarang. Semoga kau juga. ***