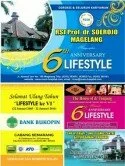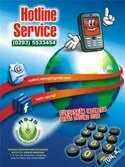Satu Hal yang Belum Kau Sebutkan
By: ann
Air mataku merembes tanpa bisa kubendung. Untuk kesekian kalinya ku rasakan kepedihan karenanya. Menyesal? Entahlah. Karena andaikata dikatakan sesal, aku masih begitu mencintainya. Mungkin juga karena aku terlalu cinta, sehingga sedikit kesedihan bisa membuatku begitu sakit. Tapi aku harus mencari cara agar pedihku ini tak menggangguku sepanjang hari.
Kepalaku berputar. Mataku berat. Efek obat tidur yang kuminum semalam, masih terasa benar. Tapi tetap harus kupaksakan berangkat kerja pagi ini, sebelum dihadang kemacetan. Sepertinya semua orang berebutan menaklukan dunia. Berangkat tergesa-gesa, pulang pun tergesa-gesa. Aku tak tahu apa yang ada di benak mereka. Bisa jadi ada yang dag dig dug karena belum menyelesaikan tugas dari atasannya kemarin, atau siapa tahu mereka dibekali dengan omelan para istri yang menagih uang belanjanya kurang? Pasti ada juga yang berbunga-bunga karena di kantormereka akan bertemu dengan pasangannya yang lain. Selingkuh?
“Ah, siapa bilang? Kita cuma sering ngobrol dan makan di kafetaria,” begitu mereka berdalih.
Tak ada yang peduli, karena semua memang punya pikiran masing-masing, dan urusan masing-masing yang harus mereka pertanggungjawabkan hari itu. Tapi waktu memang begitu cepat berputar. Hingga aku tiba di sini, setelah lelah berlari.
“Pagi, pak…” sapaku pada Pak Trimo, OB pantry senior di kantor tempatku bekerja. Kami bertemu di tangga lantai dua.
“Pagi bu Ike..” jawabnya santun. Ia termasuk OB favoritku karena wajahnya yang selalu tampak cerah. Senyumnya selalu mengembang meski ia mesti mondar-mandir meladeni permintaan teman-teman kerjaku. Satu lagi, ia paling hafal dengan minuman kesukaanku.
“Pak Trimo, tolong minumnya ya.. Saya langsung ke ruang kontrol soalnya.”
“Teh tanpa gula dengan perasan jeruk nipis, Bu?” tanyanya.
“Siip!” jawabku. Aku memang familiar dengannya. Jadi, sapaanku pun dia sudah hafal. Bahkan ia lah yang menyempatkan membeli jeruk nipis karena di pantry, selain air putih tentu, hanya ada teh dan kopi hitam. Karenanya, paling tidak dua minggu sekali aku memberinya tip untuk sekedar membeli rokok atau beras buat keluarganya di rumah.
“Baik, Bu.. Saya akan letakkan di meja Ibu seperti biasa,” jawabnya bergegas.
***
Ah, kadang-kadang aku iri dengan lelaki setengah baya itu. Ia begitu lepas berceloteh tentang anak istrinya.
“Rima tidak masuk sekolah, Bu…” begitu jawab Pak Trimo saat kutanya kabar putri sulungnya.
“Lho.. kenapa, Pak? Sakit?” tanyaku. Kudongakkan kepala dari angka-angka di meja kerjaku sore itu. Pak Trimo memang sering menungguku lembur. Sesekali celetuknya memecah hening. Jadi akupun mesti tahu diri agar tak pulang terlalu malam.
“Belum bayar iuran bulanan..” ucapnya masih dengan nada biasa. Tak kudengar nada mengeluh atau minta dikasihani. “Malu, katanya. Dia tak bisa ikut ujian kalau sampai akhir minggu ini belum dilunasi,” lanjutnya. Aku tahu, gaji pegawai rendahan seperti pak Trimo memang tak begitu besar. Paling-paling, ia mendapat sedikit tambahan dari uang lembur atau tips dari teman-temanku yang sering memintanya membeli ini-itu.
“Berapa pak?”
“Tiga bulan…”
“Bukan, uangnya..”
“Ooo…enam ratus ribu, Bu. Gimana ya, orang kecil seperti saya ini bisanya cuma minta tambahan waktu sambil pontang-panting cari pinjaman. Itupun kalau ada orang yang masih mau percaya pada saya. Soalnya, pinjaman saya kan sudah banyak, Bu..,” kulihat senyumnya mengembang tipis.
Aku mafhum. Di kota besar seperti Jakarta, dengan 4 anak, ia dan istrinya yang menjadi buruh cuci setrika, mesti pandai menjadwal pembayaran mana yang bisa dinomorduakan. Kalau perlu, dihutang. Apalagi istrinya pun mulai sakit-sakitan. Praktis, pengeluaran mereka pun menambah panjang daftar pinjaman di tetangga kiri kanan.
“Istri saya, saya larang untuk bekerja lagi, Bu. Kasihan. Mungkin ia terlalu capek. Biarlah saya yang bekerja. Saya yakin, dengan niat baik, pasti Allah kasih jalan. Kata orang, inilah saat cinta menjadi ujian…”
Aku terhenyak. Tak kusangka pak Trimo berkata sedalam itu. Kututup buku kerjaku. Aku mulai tertarik menyimaknya lebih serius.
“Maksud pak Trimo?” aku berharap bisa belajar lebih banyak.
“Maaf lho. Cinta itu kan keihlasan, ya Bu? Keihlasan kita untuk memberi tanpa berharap menerima, keihlasan kita untuk memahami istri, suami atau anak-anak kita, termasuk keihlasan untuk ‘legowo’ dan sadar dengan kekurangan diri sendiri. Jadi, saat istri saya sakit, saya harus menunjukkan bahwa bagaimanapun keadaannya, saya tetap mencintainya..”
Waduuh, so sweet!
***
Pak Trimo berkali-kali membungkuk sembari mengucap terimakasih saat kusisipkan amplop di tangannya. Tapi bukan itu yang mengusikku. Percakapanku kemarin dengan lelaki yang rambutnya mulai ditumbuhi uban itu membuatku berpikir. Mungkin ada yang salah dengan caraku mencintai Awan. Kuakui, aku teramat mencintainya. Bahkan aku tak tahu apakah aku masih bisa melanjutkan hidup jika ia benar-benar meninggalkanku. Aku bersedia melakukan apapun untuknya.
Meski kadang kurasa konyol juga. Berjuang menyenangkan orang lain, tapi kok malah tersaruk sana-sini, nyaris lalai mencintai diri sendiri. Aku ingat, setiap kali berusaha tampil prima secara fisik dan membuat bangga pasangan, rasanya malah tidak bisa menikmati diri sendiri. Apa yang bisa dibilang nikmat jika hak tinggi stiletto membuat betis diam-diam kram di waktu malam? Apa bisa disebut nyaman bila maskara di bulu mata palsu membuat kornea tersiksa? Apa enaknya melewatkan steak tuna saos lada hitam demi diet yang tak juga memberiku bentuk tubuh sempurna? Mending kalau hasilnya setimpal. Dipuji juga enggak!
Herannya, jaman sekarang banyak perempuan yang nekat operasi plastik hanya untuk menyenangkan suaminya. “Biar enggak pindah ke pelukan perempuan lain”, menjadi alasan yang paling lazim dicatut. Apologi atau ketidakpercayadirian? Wah, betapa rendahnya penghargaan diri perempuan, yang dipaksakan ikhlas untuk menyayat menjadi pseudo-masochist terhadap tubuhnya sendiri.
Tapi manusia memang punya cara berbeda dalam menilai sesuatu, juga pengharapan terhadap seseorang. Mungkin pengharapanku terlalu tinggi. Hingga aku lupa, kami adalah dua manusia dengan dua isi kepala. Kenyamananku hanya pada balutan daster lembut, sementara Awan ingin melihatku dalam lingerie seksi. Dan, dari sanalah malapetaka itu dimulai. Awan terpikat pada sosok cantik bergaun mini, lengkap dengan bibir penuh hasil kolaborasi silicon cair. Ia memporakporandakan mimpiku sebelum sampai akhir.
“Aku tak hendak menghalangimu, Awan. Kita memang tak lagi punya tujuan yang sama. Pergilah bersamanya…”
Seharusnya aku bisa mengucapkannya kala itu. Sayang, egoku berkata lain. Sepuluh butir pil penenang kutenggak sekaligus. Awan pun urung pergi. Aku merasa menang.
Tapi tidak. Kini semua harus kukembalikan pada rel yang benar. Bukankah pernikahan ditautkan untuk membahagiakan satu sama lain?
Jika Awan merasa lebih nyaman dengan perempuan itu, bukankah sama saja mengatakan bahwa ia tak bahagia bersamaku?
Aku ingat kata pak Trimo. Ada saatnya cinta diuji.
“Bu, cinta itu kan keihlasan ya? Keihlasan kita untuk memberi tanpa berharap menerima, keihlasan kita untuk memahami istri, suami atau anak-anak kita, keihlasan untuk ‘legowo’ dan sadar dengan kekurangan diri sendiri…”
Pak Trimo, besok kita harus bertemu lagi. Ada satu hal yang belum kau sebutkan.
“Cinta itu juga keihlasan melepas seseorang tanpa dendam.”***