SECUIL CATATAN DUNIA EDUKASI
 Bicara tentang pendidikan tinggi, persoalan dan tantangan yang dihadapi semakin kompleks. Perkembangan pendidikan tinggi di Indonesia tak beranjak dari masa lalu. Kalau dilihat realitasnya, pendidikan memang masih rendah ketimbang negara-negara Asia lainnya. Apalagi bila disandingkan di level dunia, Indonesia hanya berada di urutan paling buncit. Jadi pendidikan di Indonesia belum banyak kemajuan. Apa penyebabnya? Pertama, jelas ada lingkaran setan ekonomi. Sebab tingkat kemakmuran masyarakat Indonesia tak beranjak lebih cepat dari negara lain. Misalnya di era 50-an. Kala itu negara-negara dunia ketiga baru mulai menyatakan kemerdekaannya. Negara-negara tersebut mulai menjalankan model-model pembangunan yang semuanya diarahkan pada peningkatan kemakmuran.
Bicara tentang pendidikan tinggi, persoalan dan tantangan yang dihadapi semakin kompleks. Perkembangan pendidikan tinggi di Indonesia tak beranjak dari masa lalu. Kalau dilihat realitasnya, pendidikan memang masih rendah ketimbang negara-negara Asia lainnya. Apalagi bila disandingkan di level dunia, Indonesia hanya berada di urutan paling buncit. Jadi pendidikan di Indonesia belum banyak kemajuan. Apa penyebabnya? Pertama, jelas ada lingkaran setan ekonomi. Sebab tingkat kemakmuran masyarakat Indonesia tak beranjak lebih cepat dari negara lain. Misalnya di era 50-an. Kala itu negara-negara dunia ketiga baru mulai menyatakan kemerdekaannya. Negara-negara tersebut mulai menjalankan model-model pembangunan yang semuanya diarahkan pada peningkatan kemakmuran.
“Kita merdekanya lebih awal, mestinya lebih baik dari pada negara yang baru merdeka,” kata Dr. Mame Sutoko, DEA. Rektor Universitas Widyatama ini mencontohkan, pada tahun 1962 Indonesia sudah mampu menyelenggarakan Asian Games, sementara Korea masih dilanda perang saudara. Namun kenyataan berbalik 180 derajat 60 tahun kemudian. Justru kita ketinggalan jauh dari mereka. Korea telah menjelma menjadi negara maju. Mereka telah sanggup memproduksi barang-barang berteknologi tinggi. Jangankan dengan Korea, kita saja masih ketinggalan dibanding Malaysia. Padahal negeri jiran ini adalah murid kita pada medio 70-an. Dilihat dari tingkat kemakmuran, pendapatan per kapita Malaysia sudah mencapai 8 ribu dollar. Sedangkan Indonesia hanya 3 ribu dolar.
Pendidikan memang berkorelasi dengan faktor ekonomi. Sebab pendidikan bukanlah barang murah. Artinya pendidikan bukan sekedar dedikasi atau loyalitas semata seperti ajaran Ki Hajar Dewantoro. Dedikasi dan loyalitas ada batasnya. Tanpa kemampuan ekonomi berat rasanya bila membicarakan pendidikan berkualitas. Baik pendidikan dasar, menengah maupun tinggi.
Khusus pendidikan tinggi, perkembangannya masih relatif rendah ketimbang negara-negara tetangga. Bahkan lebih memprihatinkan dibanding masa lalu. Hal ini terlihat dari berbagai pemeringkatan lembaga survey independen. Seperti Time Higher Education Survey (THES), Shanghai Zia Dong, Quacquarelli Symonds, Webometric dan 4 ICU. Secara umum dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan tinggi di Indonesia berada pada urutan bawah bersama Filipina, Vietnam dan Kamboja.
KURANG KOMITMEN
Ketertinggalan ini, menurut alumnus ITB ini, terjadi lantaran ada inkonsistensi kebijakan publik. Pada awal kemerdekaan diwarnai dengan kepemimpinan liberal yang melalui Dekrit Presiden berubah sedikit demi sedikit ke arah perencanaan sentral. Kepemimpinan militer orde lama cenderung mengarah kepada ekonomi pasar yang didominasi gaya authoritarian dan kolaborasi birokrat-pengusaha pada lingkaran penguasa tertinggi. Era reformasi tetap mencerminkan ekonomi pasar dengan tuntutan demokrasi yang kurang difahami dan dihayati dengan benar. Semua itu mengakibatkan banyak praktek dan kebijakan publik yang tidak konsisten dengan cita-cita awal Republik ini.
Di sisi lain, pengambil kebijakan publik juga kurang menyadari perannya sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas dan aksesabilitas pendidikan nasional. Selama ini fokus Pemerintah hanyalah pada Perguruan Tinggi Negeri. Padahal PTN hanya menampung 30 persen populasi mahasiswa. Jadi sulit bicara peningkatan pendidikan tinggi nasional bila perguruan tinggi swasta yang menampung 70 persen student body masih bekerja dengan segala kekurangannya.
Menurut Mame, Pendidikan Tinggi Nasional tidak hanya melibatkan Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Justru komponen mayoritas pendidikan tinggi adalah Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Sayangnya proporsi APBN dapat dilihat bahwa hampir seluruh alokasi ditujukan bagi PTN. Padahal, tidak sedikit PTN ‘bersubsidi’ tak beranjak maju dan kualitasnya jauh di bawah PTS.
“Saya tidak minta bantuan dan tidak menghimbau agar PTS diberikan hak yang sama. Tapi paling tidak mahasiswanya sajalah yang diperhatikan. Mereka ini kan masa depan bangsa yang orang tuanya juga pembayar pajak dan banyak mengalami kesulitan finansial. Tidak usah bicara jauh-jauh ke Kalimantan atau Papua, di Jawa saja masih banyak yang tidak mampu melanjutkan ke perguruan tinggi,” kata Mame.
Menurut Mame, yang terjadi kini justru bea siswa untuk mahasiswa PTN naik tiga kali lipat. Sedangkan mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta hanya mendapat alokasi tidak lebih dari sepertiganya. “Ini kan diskriminasi. Padahal mereka semua sama-sama warga negara Indonesia. Seharusnya juga diperhatikan dong,” tegas Mame Sutoko.
Selain itu, menurut Mame, pemerintah juga harus mengeluarkan kebijakan tentang pembagian program studi (prodi) di PTN dan PTS. Misalnya, PTN lebih diarahkan untuk membuka prodi ilmu-ilmu eksak dan teknik yang membutuhkan modal besar. Sedangkan untuk ilmu-ilmu sosial diserahkan PTS.
“Kalau PTN juga membuka prodi yang sama, jelas PTS kalah bersaing. Kalau seperti Universitas Widayatama sudah bisa mengimbangi, tapi PTS-PTS kecil lama kelamaan akan tutup. Pemerintah harus membuat kebijakan yang pro terhadap swasta.
Perlu diingat, PTS menampung 70 persen total populasi mahasiswa,” kata Mame. Menurut undang-undang, pemerintah berkewajiban menyediakan sekolah bagi generasi baru. Hanya saja kita pun mesti memaklumi bahwa pemerintah mustahil menyediakan semuanya. Dari tingkat dasar, menengah maupun pendidikan tinggi. Oleh karena itu swasta tergerak untuk mengisi kekosongan tersebut.
Lembaga pendidikan swasta merupakan partner pemerintah. Swasta itu mandiri dalam operasionalnya. Maka untuk bisa menyediakan pendidikan yang berkualitas diperlukan manajemen, skill, dedikasi dan loyalitas. Artinya pendapatan yang diperoleh dari anak didik harus dikembalikan dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan dan lulusan. “PTS jangan hanya mementingkan income saja, tapi kualitas harus dijaga,” imbuh Mame mengingatkan.
Selain kurangnya komitmen untuk memajukan pendidikan tinggi, menurut Mame, pemerintah nampaknya tidak memahami sumber permasalahan yang dihadapi. Kenaikan anggaran pendidikan sebesar 20 % dari APBN belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Sebab anggaran ini dialokasikan pada berbagai program tidak efektif, inkonsisten dan tidak berkesinambungan.
Ditambah lagi Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi sama sekali tidak memiliki sistim perencanaan, termasuk sumber daya manusia yang dapat diandalkan. Sumber utama adalah pemikir dari Perguruan Tinggi Negeri yang bekerja paruh waktu tanpa status, kurang pemahaman ataupun komitmen yang jelas bagi pengembangan pendidikan tinggi. Isu sektor pendidikan tinggi di Indonesia saat ini nampaknya tidak berbeda dengan 40 tahun silam, bahkan bertambah dengan kesenjangannya terhadap dunia internasional.
LATAH
Sudah menjadi kebiasaan para pengambil kebijakan untuk bersikap latah dalam menanggapi perkembangan atau isu baru. World Class University (WCU) muncul sejalan dengan maraknya pemeringkatan Lembaga Pendidikan Tinggi oleh berbagai lembaga pemeringkatan independent mendorong Universitas di berbagai Negara mengejar status ‘berkelas dunia’.
Tentu meningkatkan standar mutu pada tataran internasional bukanlah hal yang buruk. Tapi perlu diingat bahwa usaha tersebut memerlukan alokasi biaya dan SDM yang besar. Pertanyaannya: apakah tolok ukur yang dituntut dalam berbagai aspek memang sesuai dalam konteks kebutuhan atau tuntutan nasional?
Dari pada berambisi mengejar status ‘berkelas dunia’ lebih baik pemerintah fokus pada kebutuhan dasar pendidikan tinggi seperti kesempatan akses bagi para lulusan pendidikan menengah atau kelangsungan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Apa artinya bisa mencapai standard universitas kelas dunia bila generasi muda yang tidak dapat melanjutkan pendidikan tinggi atau putus di tengah jalan.
Sebaiknya trade off antara kedua sisi yang sama–sama penting tersebut dapat difikirkan dengan bijak mengingat sumber daya Indonesia sangat terbatas dibandingkan dengan negara lain. Tidak harus standard WCU diterapkan atau diwajibkan bagi semua institusi karena peningkatan kualitas memerlukan pembangunan infrastruktur yang bersifat gradual tidak mungkin dilakukan secara instant sekaligus. Oki/Sugeng
 0
0 0
0 0
0
 0
0 0
0



























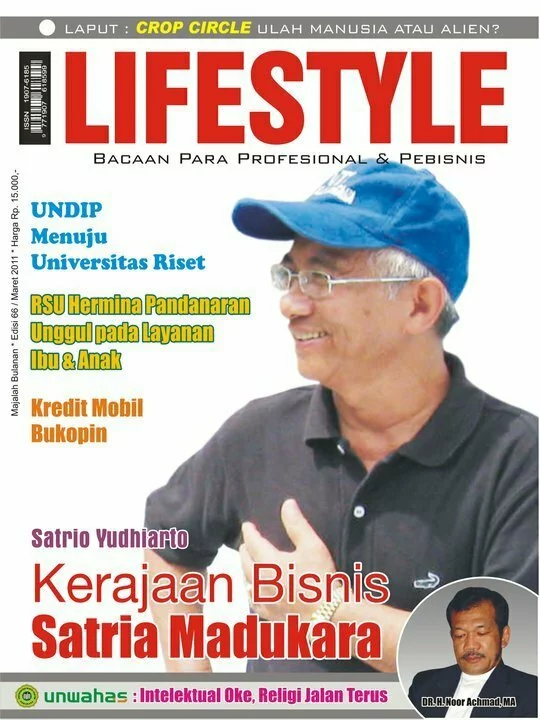






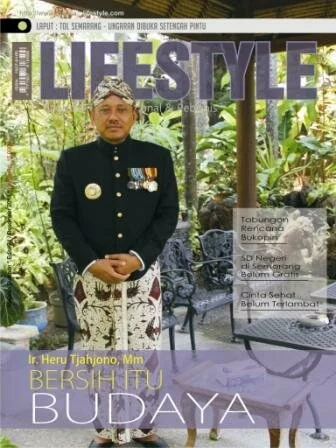
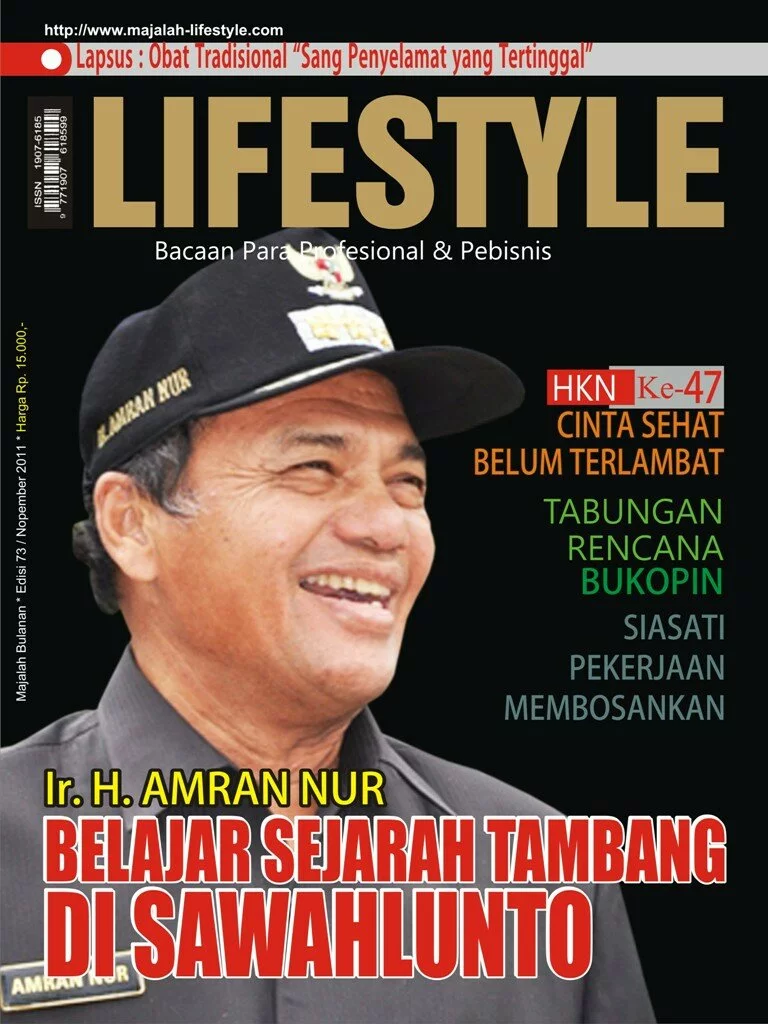



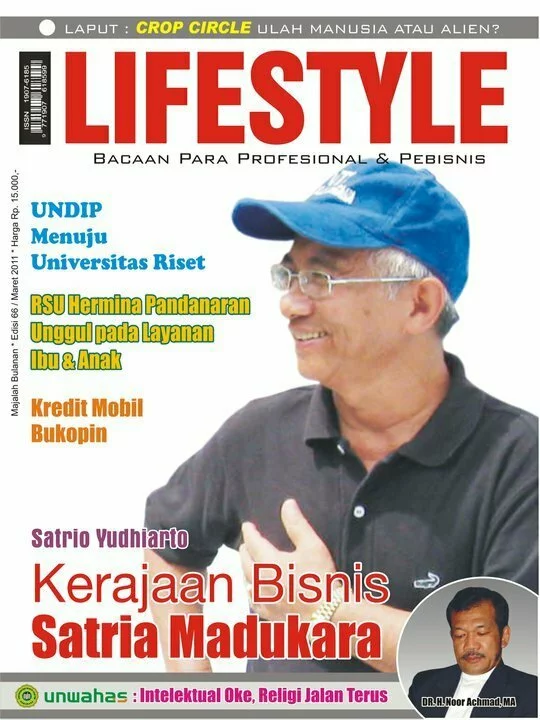



 Nilai Tukar Mata Uang Rupiah
Nilai Tukar Mata Uang Rupiah








Recent Comments